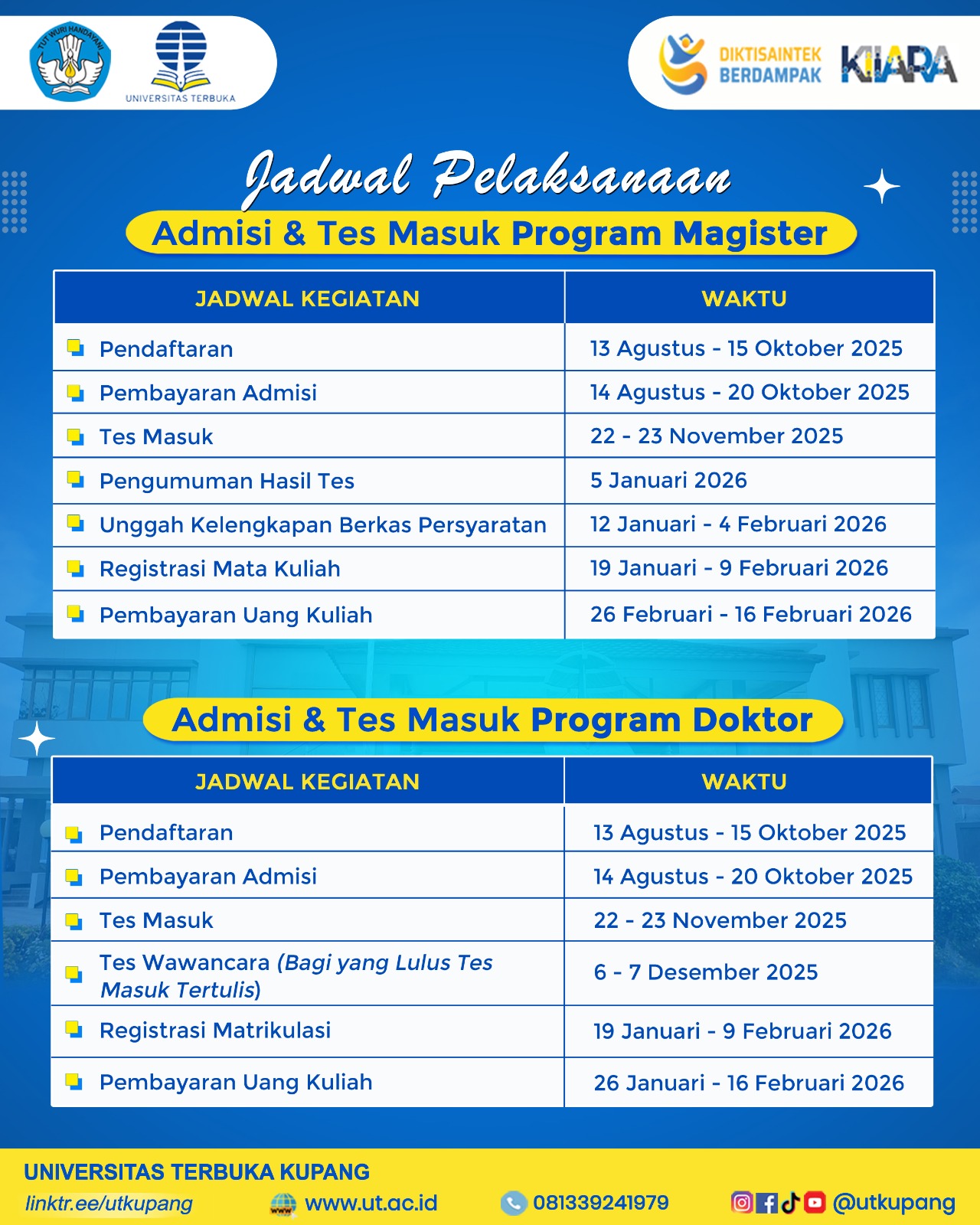Penulis: Tim | Editor: Redaksi
Menolak Banalitas Kejahatan dalam Proses Hukum
“Dimana-mana aku selalu dengar yang benar akhirnya yang menang. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan?”
Kata-kata Pramoedya Ananta Toer ini seolah menggema di tengah sunyi dan tumpulnya nurani hukum di negeri ini. Kebenaran, kata Pram, tidak turun dari langit. Ia mesti diperjuangkan. Dan di sinilah letak persoalan kita: ketika hukum tidak lagi diperjuangkan, melainkan diperdagangkan; ketika keadilan tidak ditegakkan, tetapi dinegosiasikan; dan ketika “perdamaian” dijadikan alasan untuk menutupi kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara sendiri.
Kasus penganiayaan terhadap KAS (23), warga Kelurahan Pitak, Manggarai, adalah potret kecil dari wajah hukum yang sedang kehilangan keberanian. Setelah sempat ramai diberitakan, kini kasus ini tenggelam dalam diam. Tidak banyak media yang memberitakan, tidak ada kejelasan dari institusi penegak hukum, dan tidak ada kepastian bagi korban. Di tengah ketiadaan informasi, beredar kabar bahwa kasus ini sedang “diupayakan damai” secara kekeluargaan. Kabar ini, jika benar, bukanlah kabar baik. Ia justru menjadi sinyal bahaya bagi tegaknya hukum dan moral publik di negeri ini.
Perdamaian, dalam konteks sosial Indonesia, sering dianggap jalan tengah yang bijaksana. Ia diidentikkan dengan keikhlasan, harmoni, dan penyelesaian tanpa permusuhan. Namun dalam kasus pidana yang menyangkut penganiayaan oleh aparat penegak hukum, perdamaian justru adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan. Ia menyalahi prinsip hukum, memperlemah korban, dan menodai makna tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan, bahkan lebih berat jika menyebabkan luka serius atau kematian. Ketika pelaku adalah aparat kepolisian, maka perbuatan itu tidak sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan penyalahgunaan wewenang negara. Seorang polisi, berdasarkan Kode Etik Profesi Polri (Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022), wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia, serta melindungi setiap warga dari kekerasan. Maka ketika pelaku justru aparat, penganiayaan itu bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga terhadap martabat institusi dan kepercayaan publik terhadap negara hukum.
Ironisnya, dalam praktik, banyak kasus serupa yang akhirnya “selesai” dengan jalan damai. Alasannya klasik: demi menjaga hubungan baik, demi ketenangan, demi menghindari aib, atau demi belas kasihan terhadap pelaku.
Namun alasan-alasan moral seperti ini sering kali digunakan untuk menutupi kejahatan struktural. Dalam konteks aparat, “damai” bisa menjadi cara sistemik untuk menghindari akuntabilitas. Ia bukan lagi ruang dialog sosial, melainkan alat pembebasan hukum bagi pelaku yang memiliki kekuasaan.
Dalam tataran hukum positif, upaya perdamaian semacam ini tidak memiliki dasar. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa konsep restorative justice tidak berlaku untuk tindak pidana berat, tidak berlaku jika dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan tidak berlaku jika menimbulkan korban luka berat. Kasus penganiayaan oleh anggota Polri jelas memenuhi semua kriteria itu: berat, dilakukan oleh aparat, dan menimbulkan korban luka. Dengan demikian, segala bentuk penyelesaian “kekeluargaan” tidak hanya melanggar etika hukum, tetapi juga bertentangan dengan regulasi internal Polri sendiri.
Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan oleh jaksa dalam kondisi hukum yang sah, bukan karena kesepakatan damai di luar proses peradilan. Artinya, jika penyidik atau aparat memfasilitasi perdamaian demi menghentikan perkara, maka tindakan itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran serius terhadap prinsip due process of law.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Dalam konteks sosial kita yang hierarkis, keluarga korban sering kali berada dalam posisi lemah. Mereka ditekan, dibujuk, bahkan diintimidasi agar “mengikhlaskan” demi ketenangan bersama. Uang ganti rugi, atau istilahnya “uang damai”, menjadi alat paling ampuh untuk menutup mulut korban dan mengubur kebenaran. Akibatnya, luka batin korban tidak pernah benar-benar sembuh. Mereka menanggung trauma tanpa pemulihan, sementara pelaku melenggang bebas dengan seragam dan pangkat yang sama.
Dari perspektif hak asasi manusia, praktik ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang setara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh, tindakan kekerasan oleh aparat merupakan bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang dilarang keras dalam UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada kompromi yang melemahkan prinsip pertanggungjawaban.
Apabila “perdamaian” dalam kasus seperti ini dibiarkan, maka dampaknya sistemik. Pertama, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri. Masyarakat tidak lagi melihat polisi sebagai pelindung, tetapi sebagai ancaman. Seragam polisi bukan lagi simbol keamanan, melainkan simbol kekuasaan yang bisa menindas dan tak tersentuh hukum. Kedua, praktik ini menciptakan preseden impunitas, sebuah kultur kebal hukum yang menular ke seluruh tubuh institusi. Jika satu kasus dibiarkan, maka kasus lain akan menyusul, dan perlahan-lahan hukum menjadi sekadar formalitas tanpa moralitas.
Ketiga, perdamaian semacam ini juga menghancurkan agenda besar reformasi Polri. Sejak reformasi 1998, Polri berjanji untuk menjadi institusi yang profesional dan humanis, lepas dari bayang-bayang militeristik masa lalu. Namun reformasi tidak akan pernah berhasil jika kekerasan masih dianggap hal biasa dan diselesaikan di ruang gelap melalui “uang damai”. Reformasi bukan soal mengganti seragam atau jargon, tetapi soal membangun etika baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum, bukan objek kekuasaan.
Keempat, praktik perdamaian juga berbahaya bagi sistem keadilan itu sendiri. Ia menumbuhkan banalitas kejahatan, yakni kondisi ketika kejahatan tidak lagi dianggap luar biasa, tetapi menjadi sesuatu yang biasa. Konsep “banalitas kejahatan” ini pernah dikemukakan oleh Hannah Arendt ketika ia menulis tentang kejahatan Nazi.
Menurut Arendt, kejahatan menjadi banal ketika pelaku tidak lagi merasa bersalah, karena sistem membuatnya tampak normal. Dalam konteks kita, perdamaian yang menutupi kekerasan aparat justru menjadikan kejahatan itu tampak sah dan lumrah.
Akhirnya, kita perlu bertanya: sampai kapan keadilan di negeri ini bisa dibeli dengan sejumlah uang? Sampai kapan korban harus diam karena takut pada seragam? Dan sampai kapan kita membiarkan hukum dikendalikan oleh rasa sungkan dan kompromi moral?
Menolak perdamaian dalam kasus penganiayaan bukan berarti menolak nilai kekeluargaan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab sosial, karena hanya dengan menegakkan hukum secara tegas, kita bisa menyelamatkan masa depan institusi kepolisian dan menjaga martabat kemanusiaan.
Keluarga korban harus didukung oleh masyarakat, oleh organisasi sipil, dan oleh media untuk menolak segala bentuk perdamaian yang mencederai keadilan. Divisi Propam Polri mesti bertindak transparan, independen, dan menolak intervensi apa pun dalam proses hukum. Sementara publik perlu terus mengawasi, menulis, bersuara, dan memastikan bahwa kasus ini tidak menghilang dalam senyap.
Keadilan bukan hadiah yang datang dari langit, ia hasil dari perjuangan. Kita memang memilih jalan yang lebih berat, tetapi itulah satu-satunya jalan yang benar. Jika kita membiarkan perdamaian menutup luka, maka kita sedang membangun masa depan di atas kebohongan. Namun jika kita menolak perdamaian yang palsu, maka kita sedang memperjuangkan kebenaran yang hakiki: bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum, dan tidak ada perdamaian yang lebih suci daripada keadilan itu sendiri.(*)
Opini ini ditulis oleh Heraklitus Efridus (Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ruteng)